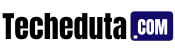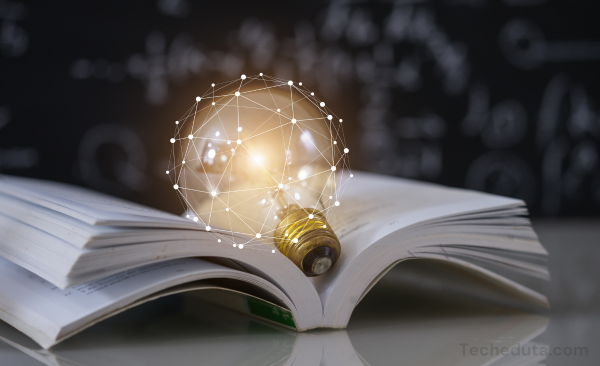Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan individu dan bangsa. Namun, pengertian pendidikan tidak selalu satu makna. Banyak ahli telah mengemukakan pandangannya tentang apa itu pendidikan, sesuai dengan latar belakang ilmu dan pemikirannya masing-masing. Dengan memahami pengertian pendidikan dari berbagai sudut pandang, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang fungsi serta tujuan pendidikan dalam kehidupan manusia.
1. Pengertian Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara
Ki Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan Indonesia, memiliki pandangan yang sangat filosofis dan humanis mengenai pendidikan. Menurut beliau, pendidikan adalah usaha untuk menumbuhkan budi pekerti (karakter), pikiran (intelektual), dan jasmani anak secara seimbang, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ia juga sangat menekankan bahwa pendidikan bukan semata-mata soal mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih pada proses pembentukan karakter dan kepribadian. Prinsip terkenal yang beliau usung adalah “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Konsep ini menjadi dasar filosofi pendidikan nasional Indonesia hingga saat ini. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan, bukan mengekang, dan bertujuan menciptakan manusia yang merdeka lahir dan batin.
2. Pandangan Paulo Freire tentang Pendidikan
Paulo Freire, seorang filsuf dan pendidik asal Brasil, dikenal luas melalui gagasannya tentang pedagogy of the oppressed atau pedagogi kaum tertindas. Ia melihat pendidikan bukan hanya sebagai proses transfer pengetahuan dari guru ke murid, melainkan sebagai alat pembebasan manusia. Menurut Freire, sistem pendidikan tradisional cenderung menggunakan pendekatan “banking system”, di mana murid diperlakukan seperti celengan kosong yang harus diisi oleh guru. Ia menentang keras metode ini karena dianggap pasif dan menindas. Sebaliknya, Freire mendorong pendidikan dialogis yang melibatkan interaksi dua arah, di mana murid dan guru saling belajar satu sama lain. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran kritis (critical consciousness) agar peserta didik mampu mengenali ketidakadilan sosial dan berani mengambil tindakan untuk mengubahnya. Bagi Freire, pendidikan yang sejati adalah proses emansipasi, membebaskan pikiran dan membuka jalan menuju keadilan sosial.
3. Definisi Pendidikan Menurut John Dewey
John Dewey, seorang filsuf dan pendidik asal Amerika Serikat, dikenal sebagai tokoh utama dalam aliran progresivisme pendidikan. Menurut Dewey, pendidikan adalah proses pertumbuhan yang terus menerus, di mana pengalaman masa lalu digunakan untuk membentuk pengalaman masa depan. Ia menolak konsep pendidikan yang bersifat kaku dan berpusat pada guru. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya learning by doing atau belajar melalui pengalaman nyata. Dewey percaya bahwa sekolah seharusnya menjadi laboratorium kehidupan, tempat siswa belajar memecahkan masalah, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Bagi Dewey, pendidikan bukan hanya untuk mengisi otak dengan fakta, tetapi untuk membentuk individu yang mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokratis. Ia juga menekankan bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan siswa dan bersifat kontekstual. Pemikiran Dewey hingga kini masih menjadi landasan penting dalam praktik pendidikan modern yang lebih aktif, kreatif, dan partisipatif.
Pengertian Pendidikan Menurut Undang-Undang di Indonesia
Dalam konteks hukum di Indonesia, pengertian pendidikan secara resmi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi ini menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai moral. Pendidikan dipandang sebagai proses holistik yang bertujuan menciptakan manusia seutuhnya. Dengan dasar hukum ini, sistem pendidikan nasional dirancang untuk menyelaraskan kebutuhan individu dan tuntutan pembangunan nasional secara berkelanjutan.
5. Perbandingan Pemikiran Para Ahli
Dari berbagai pandangan ahli yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki makna yang luas dan kompleks. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya budi pekerti dan kebebasan dalam belajar, sementara Paulo Freire melihat pendidikan sebagai alat pembebasan dari penindasan. Di sisi lain, John Dewey mengajak kita melihat pendidikan sebagai proses pengalaman yang terus berkembang, dan Undang-Undang di Indonesia memberikan definisi formal yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, dan keterampilan. Meskipun pendekatan mereka berbeda, semua pandangan ini memiliki benang merah yang sama: pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, kesadaran sosial, dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan. Dengan memahami berbagai perspektif ini, kita dapat melihat bahwa pendidikan ideal adalah yang mampu memberdayakan individu secara utuh baik secara pribadi, sosial, maupun intelektual dan menciptakan generasi yang cerdas serta bermartabat.
Baca juga: Pengertian Pembelajaran
Kesimpulan
Sebagai pilar utama dalam pembangunan manusia, pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk masa depan individu dan bangsa. Melalui berbagai sudut pandang para ahli, kita dapat memahami bahwa pendidikan bukan hanya proses belajar-mengajar, melainkan juga proses memanusiakan manusia. Setiap gagasan dari para tokoh seperti Ki Hajar Dewantara, Paulo Freire, dan John Dewey hingga perumusan formal dalam undang-undang, memberi kita wawasan berharga tentang nilai dan tujuan pendidikan yang ideal. Dengan meresapi beragam perspektif ini, semoga kita dapat menerapkan sistem pendidikan yang lebih holistik, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman.